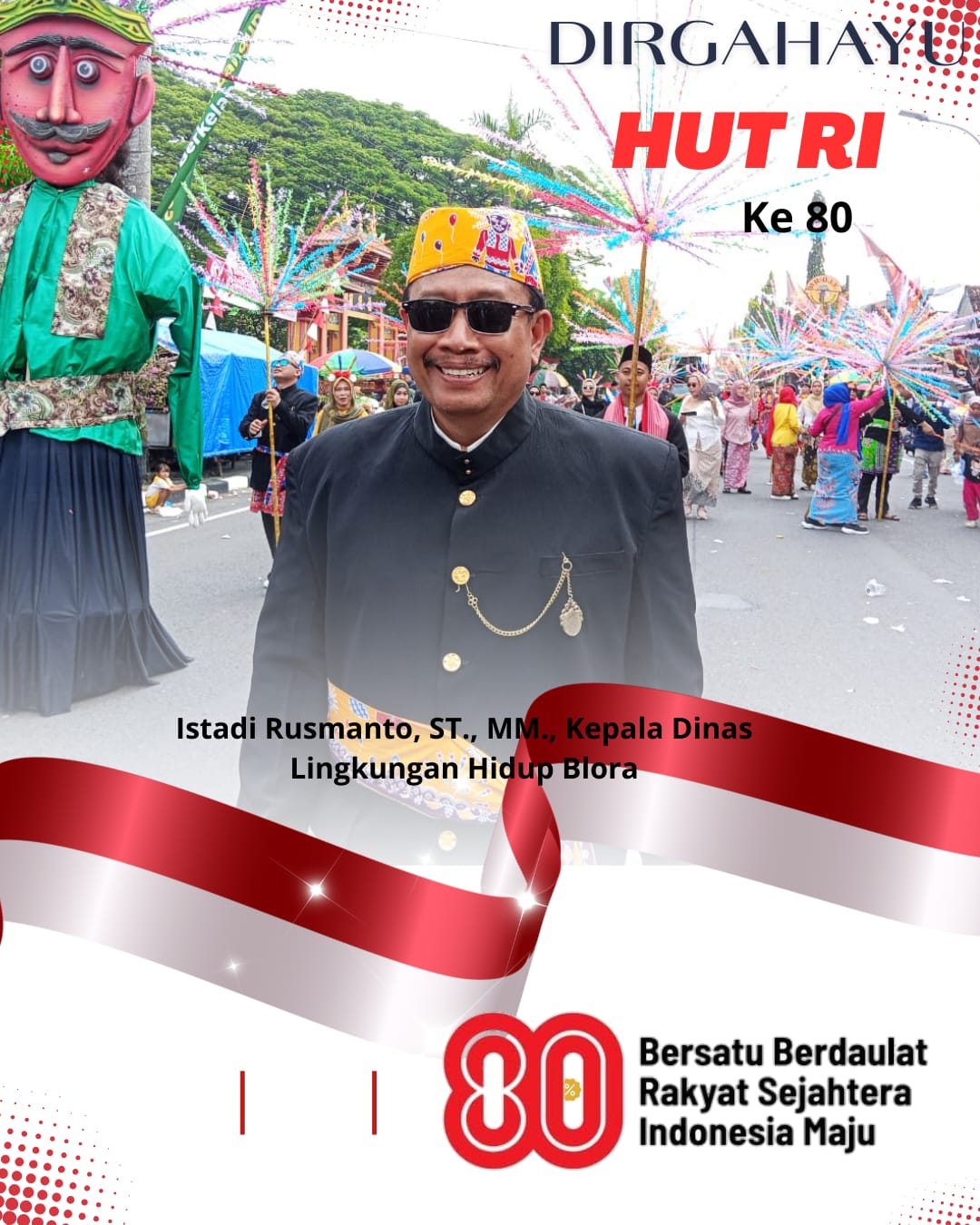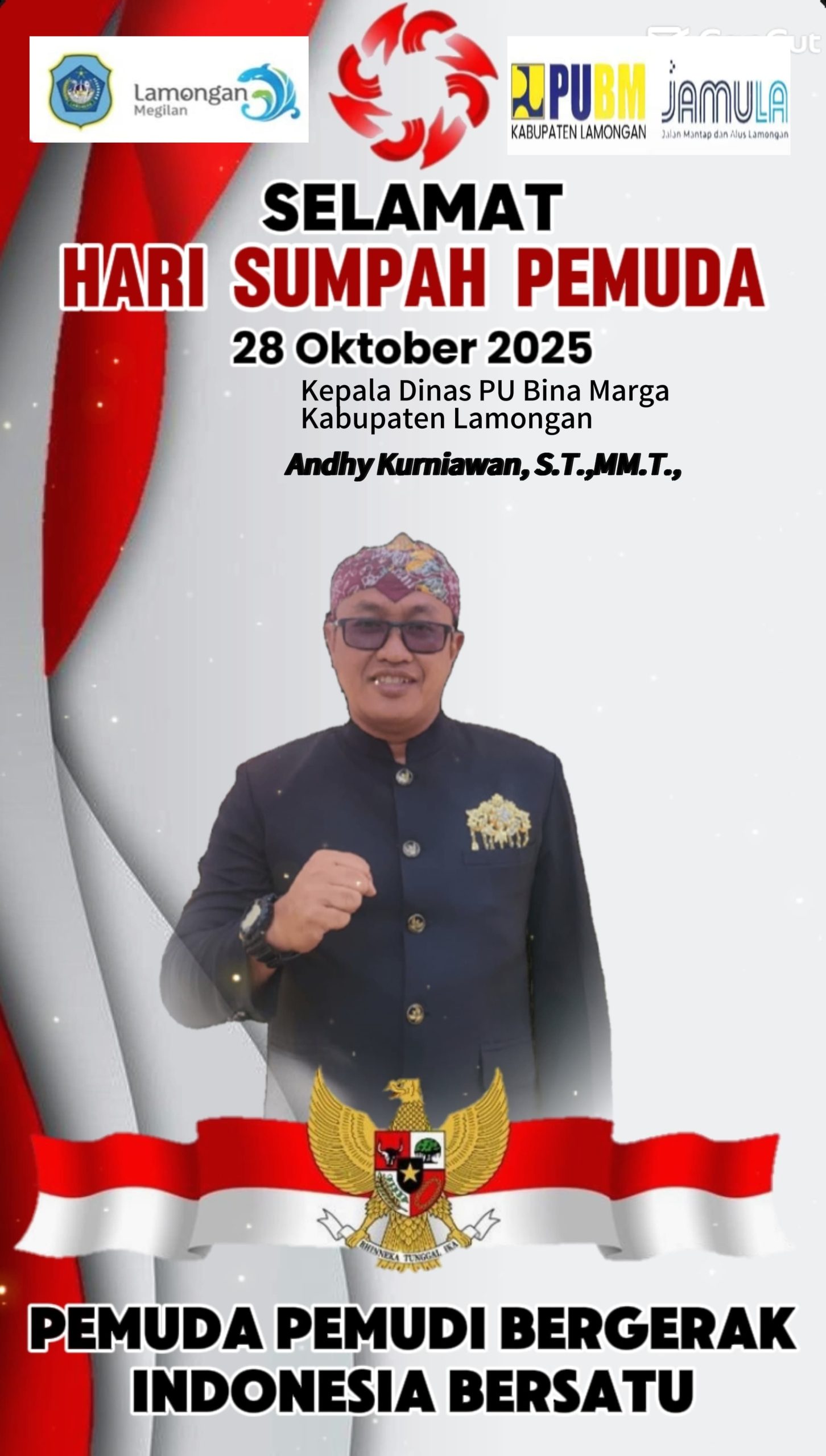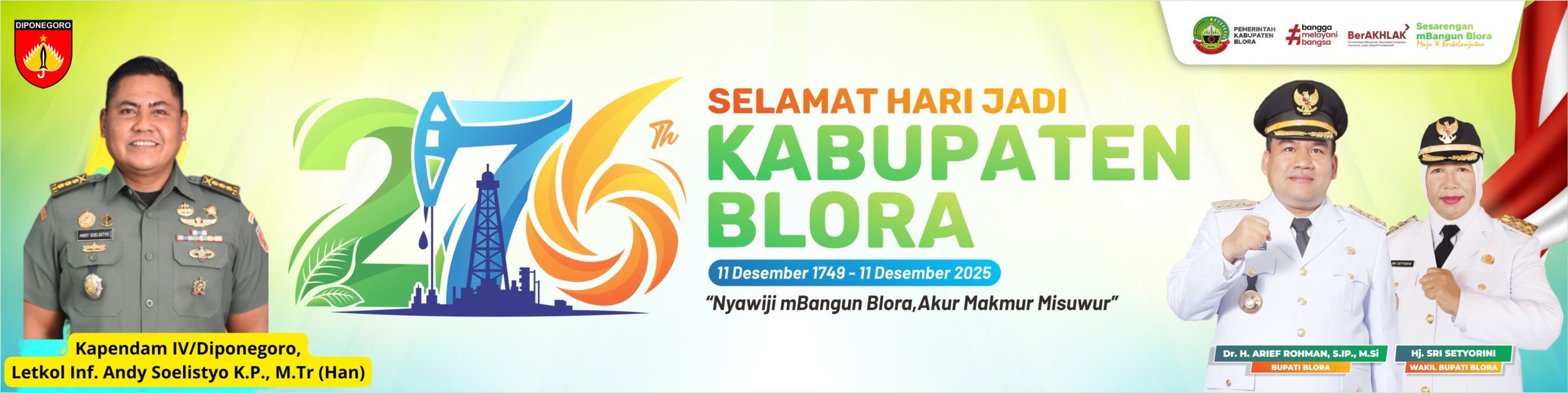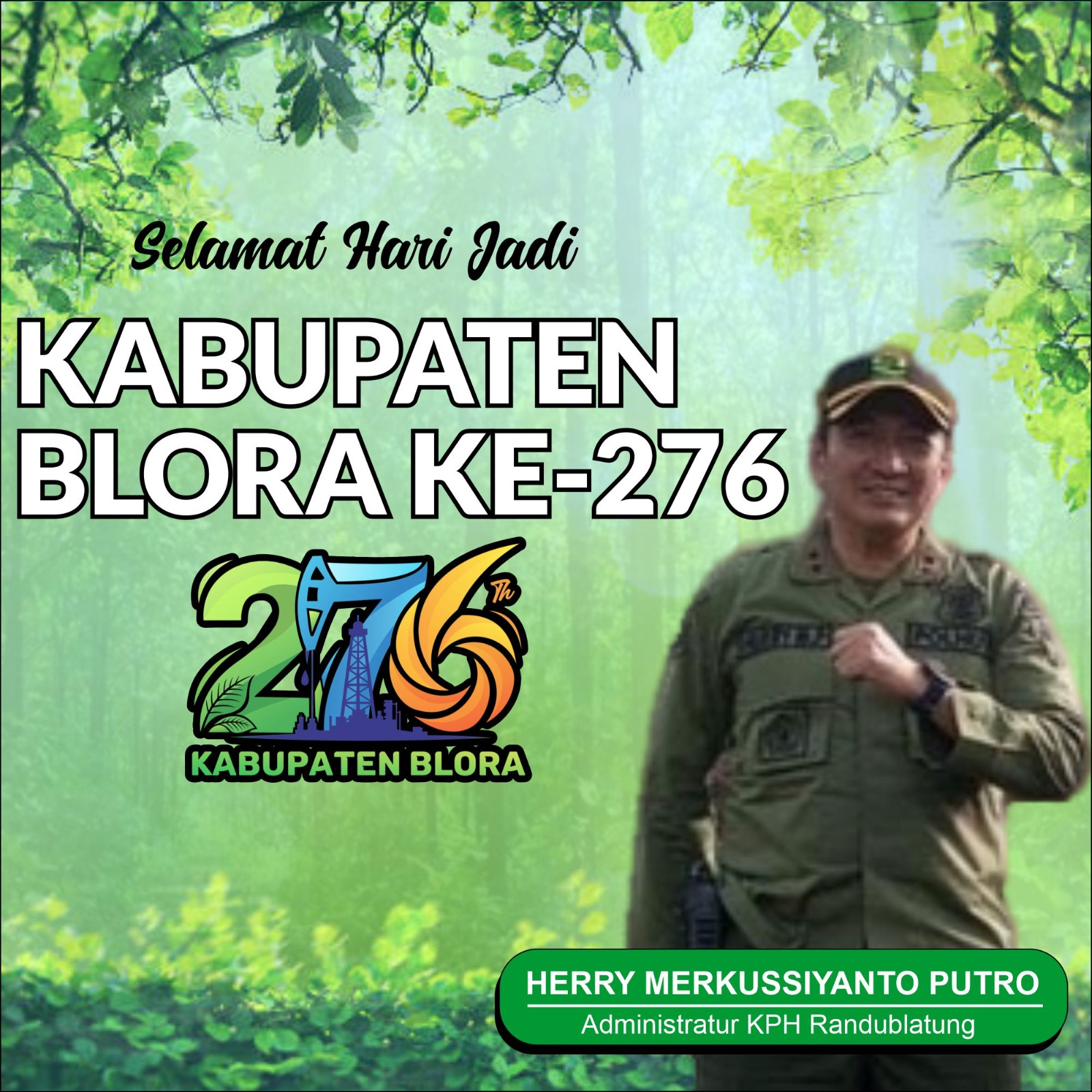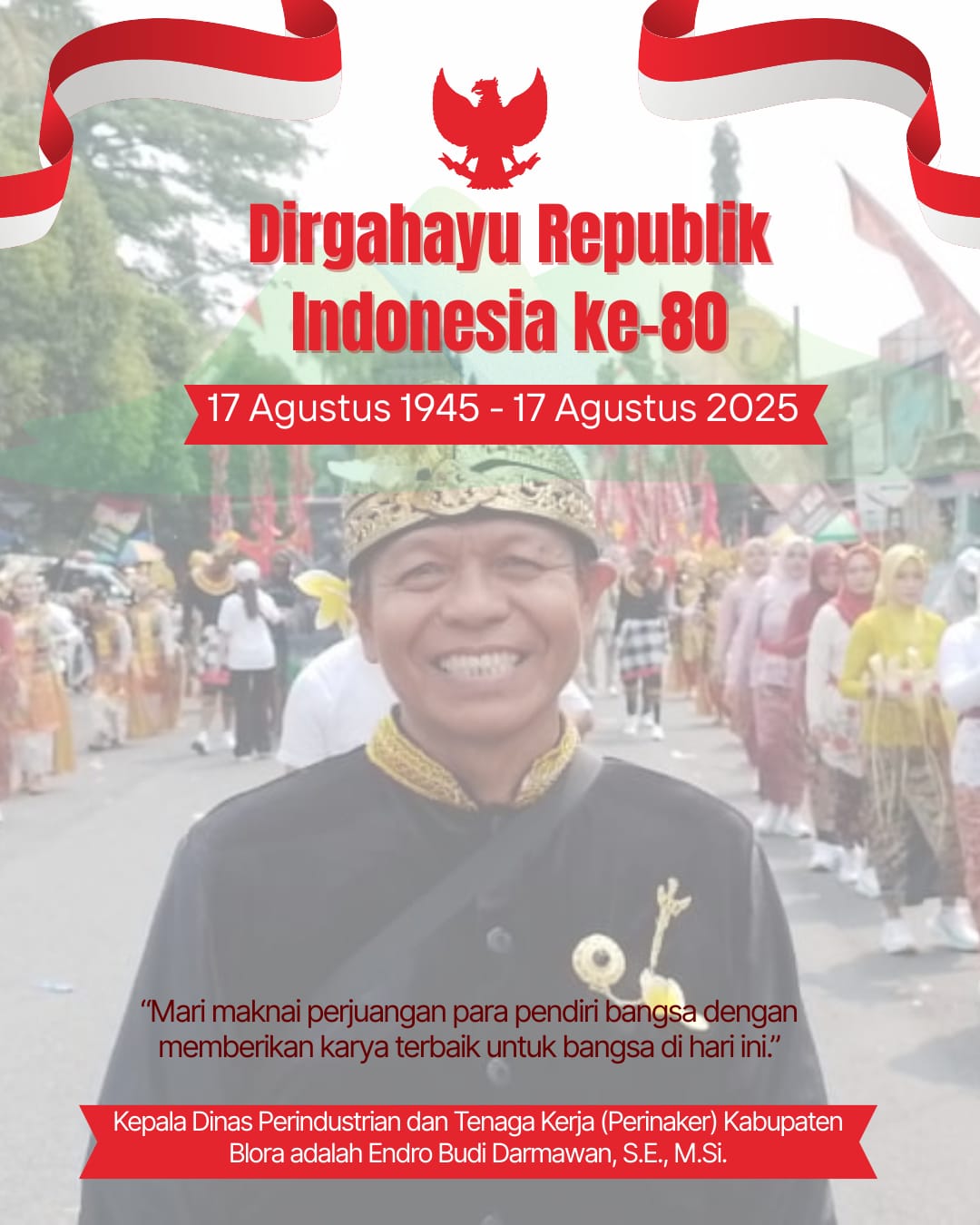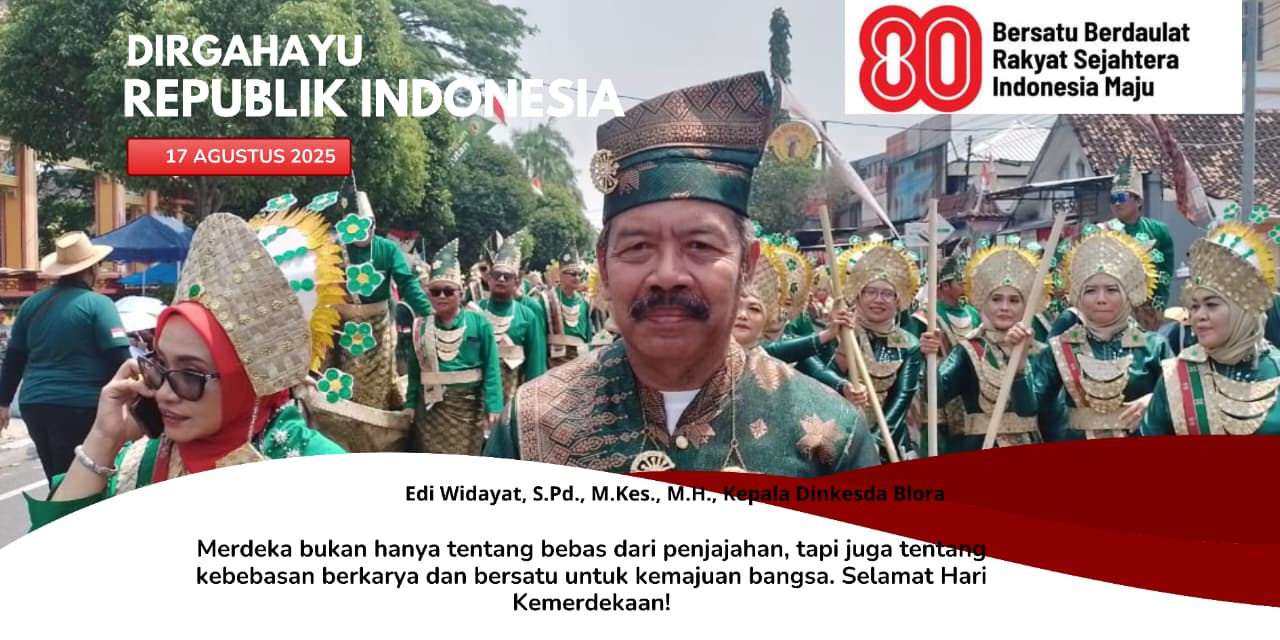Beberapa hari lalu, sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Blora menggelar aksi penolakan terhadap rencana pendirian kampus Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di Kabupaten Blora. Jumlah peserta aksi memang tidak besar—belasan orang saja. Argumen mereka pun tampak sederhana, antara lain soal hibah lahan dan potensi ketimpangan dengan perguruan tinggi swasta (PTS) lokal.
Di mata sebagian orang, aksi ini mungkin terlihat “gagal” secara komunikasi. Ada peserta yang terlihat gugup saat diwawancarai wartawan, penjelasan yang kurang sistematis, dan tampilan visual yang mudah disalahpahami. Namun, apa pun bentuk dan kualitas penyampaiannya, aksi ini adalah bagian dari praktik demokrasi: menyampaikan pendapat di ruang publik atas suatu kebijakan yang menyangkut masa depan daerah. Itu seharusnya dihargai, bukan dihakimi.
Sayangnya, bukan substansi pendapat yang kemudian dibicarakan masyarakat, melainkan tampilan dan personal para mahasiswa. Ruang publik digital berubah menjadi arena perundungan massal.
Potongan video dari aksi tersebut—terutama cuplikan wawancara yang tampak tidak meyakinkan—cepat menyebar di TikTok dan platform media sosial lain. Ribuan komentar membanjiri unggahan tersebut. Namun, alih-alih membahas apakah penolakan terhadap UNY punya dasar yang layak dipertimbangkan, mayoritas komentar justru bernada ejekan, cemoohan, hingga penghinaan personal terhadap mahasiswa yang tampil dalam video.
Penampilan fisik, cara berbicara, bahkan kampus asal mahasiswa tersebut menjadi sasaran olok-olok kolektif. Tidak sedikit yang menuliskan komentar bernada superior: “Makanya perlu kampus negeri, biar nggak gitu amat,” atau “Kalau begini kualitasnya, pantes kampusnya nggak maju.” Publik tidak lagi membahas substansi, melainkan merendahkan pribadi dan institusi yang berbeda pandangan. Yang terjadi bukan diskusi publik, melainkan pengadilan massal tanpa hakim dan tanpa ruang pembelaan.
Dalam banyak konflik sosial, framing memainkan peran kunci. Begitu juga dalam kasus ini. Ada indikasi bahwa potongan video tertentu—khususnya yang menampilkan ketidaksiapan mahasiswa—disebarkan dengan intensitas tinggi oleh akun-akun yang sebelumnya menunjukkan dukungan terhadap pendirian UNY. Narasi yang muncul pun cenderung menyeragam: mahasiswa terlihat “asal bicara”, kampus mereka dianggap “tidak layak bersuara”, dan akhirnya dibingkai sebagai bukti bahwa Blora memang butuh kampus negeri “yang berkualitas”.
Ketika framing semacam ini dibarengi dengan kekuatan algoritma TikTok yang mendorong konten viral berbasis emosi, maka yang terjadi adalah pembentukan opini publik yang tidak lagi objektif. Kritik dianggap sebagai lelucon, suara oposisi dilecehkan, dan lawan pendapat dipermalukan di hadapan massa. Ini adalah bentuk pembungkaman yang halus namun efektif. Bukan dengan kekerasan fisik, tapi dengan tekanan sosial dan stigma digital. Demokrasi tampak hidup, tapi sebenarnya penuh luka.
Perundungan terhadap mahasiswa Blora ini mencerminkan budaya digital kita yang belum dewasa. Media sosial kini menjadi panggung pertunjukan massal, di mana mereka yang tampil tidak sesuai ekspektasi bisa dengan mudah dijadikan bahan olok-olok. Algoritma mendorong konten yang memicu tawa, kemarahan, atau ejekan. Akibatnya, ketidaksempurnaan seseorang lebih cepat viral daripada kebenaran pendapatnya.
Jika ini dibiarkan, kita sedang membesarkan generasi yang lebih sibuk mencari celah untuk mengejek ketimbang mencari titik temu dalam perbedaan.
Demokrasi bukan hanya soal kebebasan berbicara, tapi juga kesediaan untuk mendengar. Ketika perbedaan pendapat dibalas dengan pembunuhan karakter, kita sedang mengalami degradasi serius dalam kehidupan demokrasi. Mahasiswa yang turun ke jalan, terlepas dari kualitas argumennya, adalah simbol keberanian menyuarakan pendapat. Ketika mereka dibully habis-habisan, pesan yang sampai ke generasi muda adalah: jangan bersuara jika tidak siap dihancurkan. Ini pesan yang salah, dan membahayakan masa depan kebebasan sipil.
Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk mendukung atau menolak pendirian kampus negeri di Blora. Bukan pula untuk membela kelompok mahasiswa tertentu atau kampus tempat mereka belajar. Ini adalah ajakan untuk kita semua berkaca: apakah ruang publik kita masih memberi tempat bagi keberanian menyuarakan pendapat, atau justru menakut-nakuti siapa pun yang berbeda agar diam?
Mari kita jaga ruang publik, baik di jalanan maupun di layar ponsel, agar tetap sehat, adil, dan manusiawi. Sebab tanpa itu, demokrasi kita akan tampak hidup—namun sejatinya sedang sekarat.
Oleh: Dwi Giatno
Penulis adalah Ketua Umum Pengurus Cabang IKA-PMII Kabupaten Blora dan Sekretaris Lakpesdam PCNU Blora.
*Opini di atas merupakan tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab dari Analisajatim.id