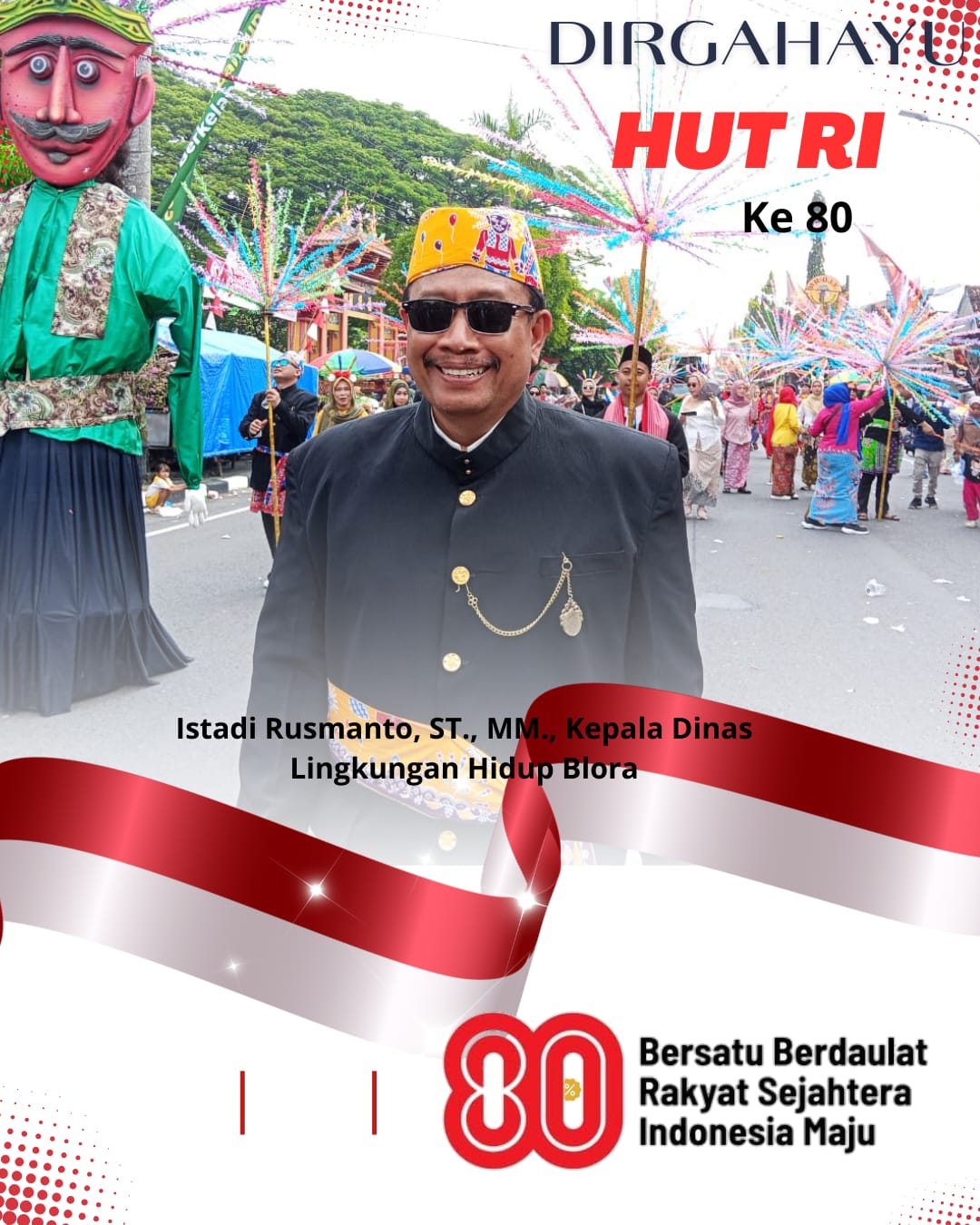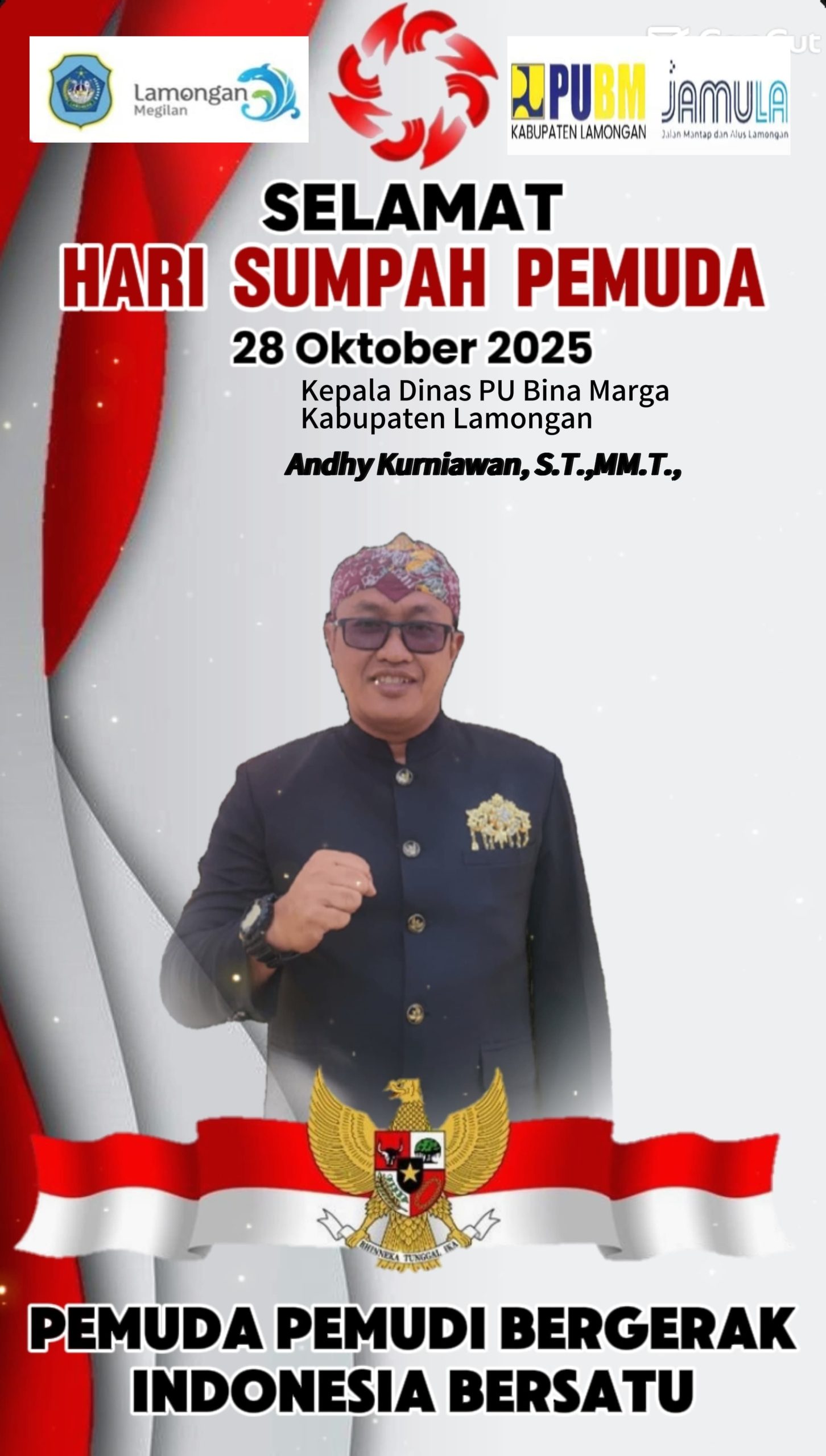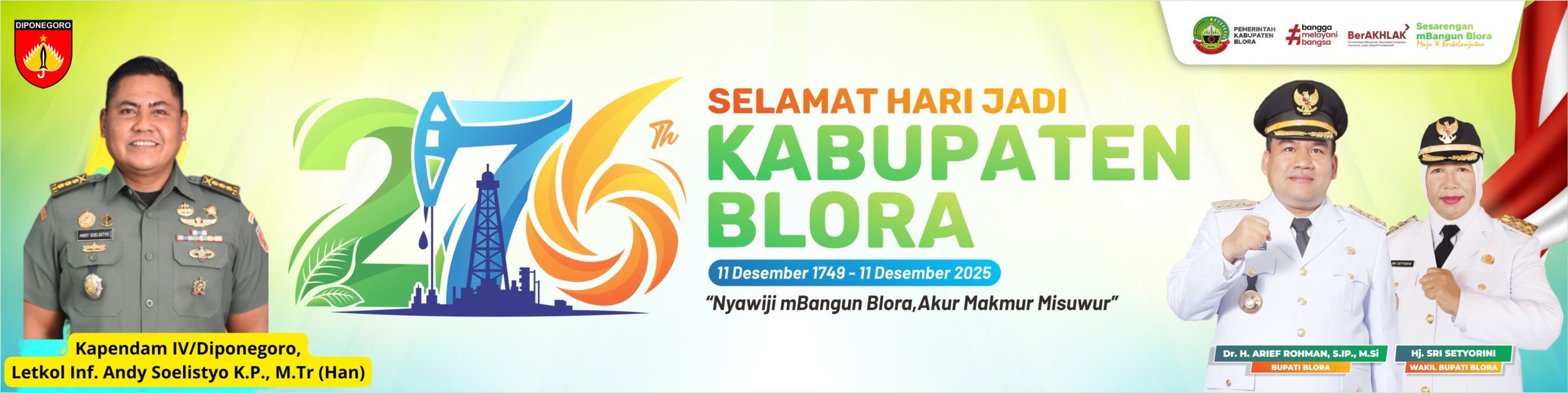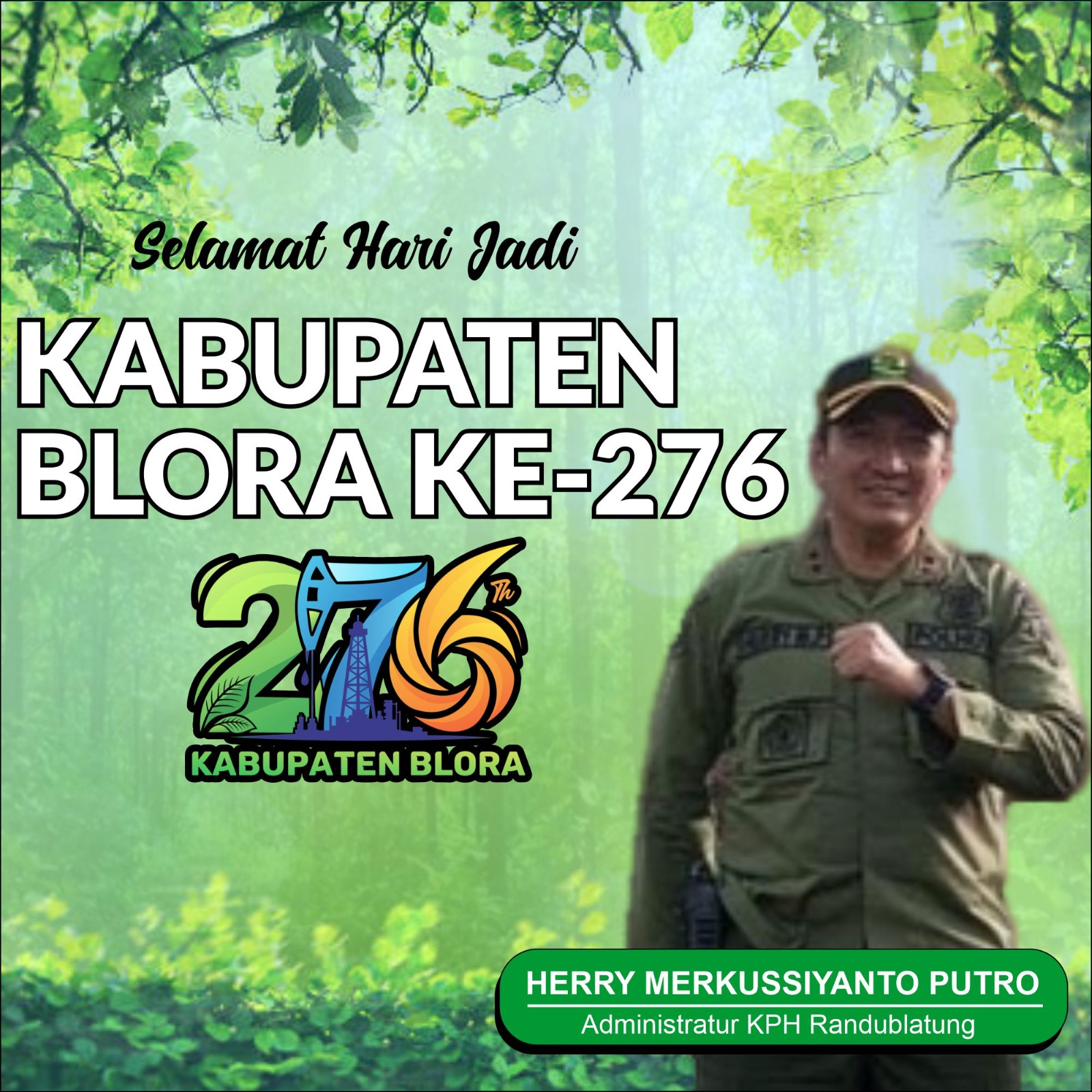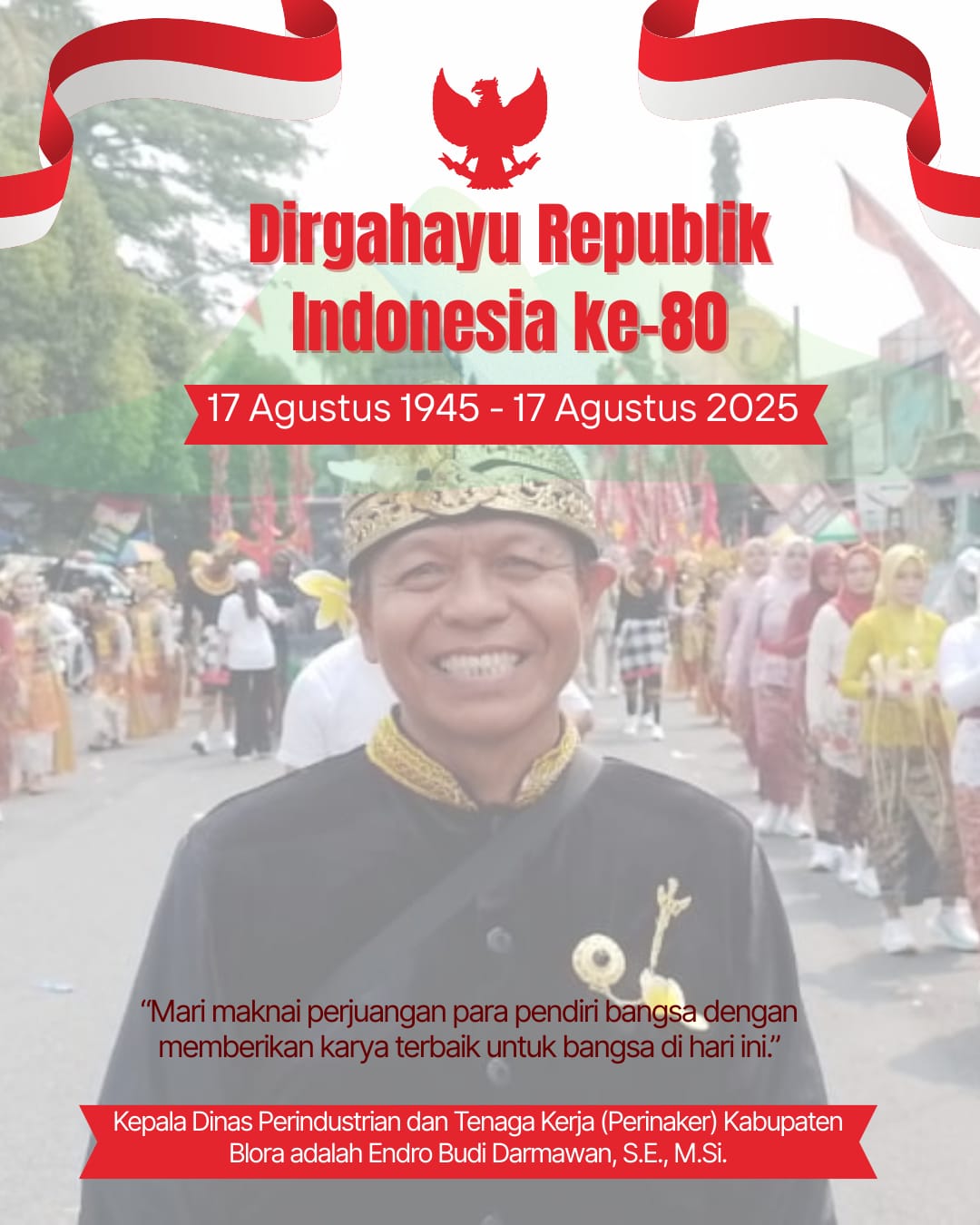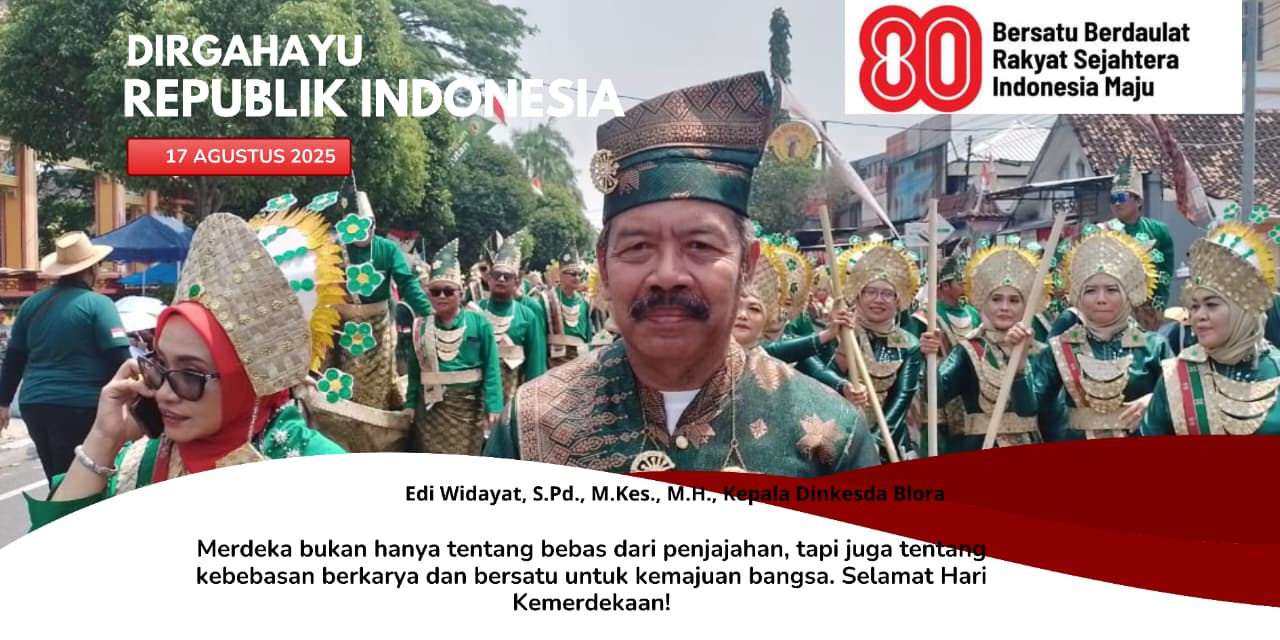Lamongan|Analisajatim.id—
Dalam perbincangan sehari-hari, politik sering kali diasosiasikan dengan kekotoran, tipu daya, dan intrik kekuasaan. Imaji semacam ini membekas kuat dalam benak publik, bahkan menjadi semacam dogma yang tak lagi dipertanyakan. Namun benarkah politik itu inheren kotor? Ataukah persepsi tersebut justru lahir dari ketidakhadiran publik dalam ruang-ruang politik, yang pada akhirnya menciptakan distorsi makna terhadap politik itu sendiri?
Politik, dalam akar katanya berasal dari bahasa Yunani, polis — yang berarti kota atau negara-kota. Dari sinilah muncul kata politikē, yang berarti “urusan kota” atau seni mengelola masyarakat.

Sesungguhnya, politik adalah instrumen mulia yang bertujuan mengatur kehidupan bersama secara adil, demokratis, dan berkeadaban. Ia adalah ruang deliberatif tempat nilai-nilai publik dinegosiasikan, kepentingan dikompromikan, dan keputusan kolektif diambil. Yang membuatnya tampak tercemar bukanlah esensinya, melainkan praktik yang terjadi ketika kekuasaan dijalankan tanpa kontrol sosial yang memadai—dan lebih parah lagi, ketika rakyat memilih menarik diri dari proses tersebut.
Tokoh seperti Plato dan Aristoteles adalah pionir dalam merumuskan kerangka berpikir politik. Plato dalam The Republic membayangkan sistem pemerintahan ideal yang dijalankan oleh para filsuf, sementara Aristoteles dalam Politics menegaskan bahwa manusia adalah “zoon politikon” — makhluk yang kodratnya adalah hidup berpolitik. Artinya, politik bukanlah alat manipulasi, tetapi wadah bagi manusia untuk mencapai kebaikan bersama (bonum commune).
Politik sebagai Ruang Publik yang Terabaikan
Dalam sistem demokrasi, politik seharusnya menjadi wahana partisipasi aktif warga negara. Akan tetapi, di banyak konteks, demokrasi telah mengalami reduksi menjadi sekadar prosedur elektoral lima tahunan. Di luar momentum pemilu, keterlibatan publik dalam proses politik nyaris nihil. Rakyat menjadi sekadar penonton, sementara panggung politik didominasi elite yang memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi dan informasi.
Kekosongan ini menciptakan situasi yang rentan terhadap disfungsi demokrasi. Di sinilah akar dari stigma “politik kotor” itu bertumbuh. Padahal, jika ditilik secara lebih jernih, yang kita hadapi bukanlah kekotoran politik sebagai sistem, melainkan absennya kontrol warga terhadap mekanisme pengambilan keputusan politik. Dengan kata lain, kita menyaksikan efek dari demokrasi tanpa demos: sistem berjalan, tetapi rakyat menghilang.
Menyalahkan Sistem atau Mendidik Partisipasi?
Alih-alih perpetuasi apatisme, semestinya kita mulai mengadopsi pendekatan yang lebih reflektif. Menyalahkan politik sebagai sesuatu yang kotor adalah bentuk simplifikasi problem. Yang perlu dilakukan bukan menjauhi politik, melainkan mengintervensi politik dengan cara-cara yang etis, kritis, dan partisipatif.
Melek politik dalam konteks ini tidak sebatas memahami proses elektoral atau mengenali aktor-aktor politik, tetapi mencakup kesadaran kritis terhadap bagaimana kekuasaan bekerja, bagaimana kebijakan publik dibentuk, dan bagaimana rakyat dapat memengaruhi arah perubahan. Paulo Freire, dalam Pedagogy of the Oppressed, menyebut ini sebagai bentuk “kesadaran politis” yang memungkinkan masyarakat tak sekadar menjadi objek kebijakan, tetapi subjek yang aktif menentukan nasib kolektifnya.
Anak Muda dan Urgensi Partisipasi Demokratis
Kelompok muda memiliki peran strategis dalam revitalisasi demokrasi. Namun, sayangnya, banyak dari mereka yang justru terjebak dalam sikap sinis terhadap politik. Narasi “semua politisi sama saja” atau “suara kita tidak akan mengubah apa pun” menjadi semacam pembenaran atas sikap pasif dan keterputusan dari ruang publik. Padahal, demokrasi hanya bisa bertahan jika ada keterlibatan terus-menerus dari warganya, termasuk generasi muda yang membawa energi, gagasan baru, dan keberanian moral.
Kita memerlukan generasi baru politisi, aktivis, dan intelektual publik yang bukan hanya ingin duduk di ruang kekuasaan, tetapi juga memahami urgensi tanggung jawab etis terhadap rakyat. Melek politik dalam pengertian ini adalah jalan menuju perbaikan struktur politik itu sendiri. Bukan melalui penolakan total, tetapi melalui partisipasi yang sadar dan terinformasi.
Politik Tak Pernah Netral, Maka Rakyat Tak Boleh Apatis
Dalam konteks relasi kuasa, tidak ada ruang yang benar-benar netral. Ketika rakyat diam, kekuasaan tidak berhenti bekerja—ia justru semakin leluasa menentukan arah kebijakan tanpa pertanggungjawaban publik. Ketika politik dibiarkan hanya menjadi arena transaksi elite, maka nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberpihakan pada rakyat mudah tergadaikan.
Apatisme bukanlah bentuk netralitas; ia adalah bentuk pengunduran diri dari tanggung jawab warga negara. Dengan kata lain, sikap “bukan urusan saya” dalam politik justru memperbesar kemungkinan terjadinya penyimpangan. Karena itu, buta politik bukan hanya sebuah kekeliruan sikap, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap masa depan demokrasi.
Rekonstruksi Kesadaran Kewargaan
Sudah saatnya kita mendekonstruksi narasi usang bahwa politik adalah kotor dan penuh tipu daya. Narasi tersebut telah melahirkan generasi yang enggan terlibat, padahal keterlibatan itulah yang diperlukan untuk membersihkan dan menata kembali ruang politik kita.
Melek politik bukan sekadar ajakan moral, melainkan kebutuhan mendesak dalam konteks demokrasi yang sehat. Karena sejatinya, politik tidak pernah benar-benar kotor. Ia hanya terlalu lama kita tinggalkan. Dan ketika rakyat memilih diam, kekuasaan berjalan tanpa arah etis.
Jika kita mencintai negara ini, maka keterlibatan dalam politik bukanlah pilihan, melainkan kewajiban.
Editor :Nur
Disusun : Mastono S. Pd
Published Red